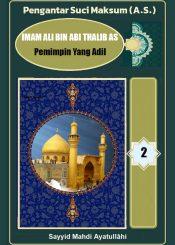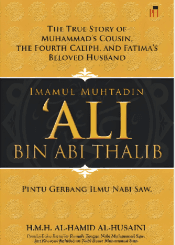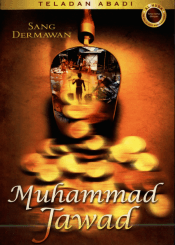Imam Ali, Ilmu Nahwu dan Filsafat
Imam Ali, Ilmu Nahwu dan Filsafat
Author :
Elka
0 Vote
324 View
Segala sesuatu memiliki lapisan luar dan dalam. Ada eksternal dan internal, kulit dan isi, zhahir dan batin, konsep dan realita, juga materi dan non-materi. Hal itu menunjukkan betapa sesuatu tidak bisa saja difahami secara artifisial, sementara melupakan substansi. Tidak bisa memaknai suatu objek hanya dari satu perspektif, lalu mengabaikan kemungkinan perspektif lain. Lapisan luar-dalam meniscayakan probabilitas, keserbamungkinan. Titik tolak ini akan melahirkan konsiderasi atas pelbagai fakta; ilmiah, maupun non-Ilmiah. Betapa al-Quran bukan hanya dapat dimaknai secara tekstual, namun juga memberi ruang yang cukup untuk mengadaptasikannya secara kontekstual. Al-Quran dapat diciduk oleh pendahaga ilmu, apapun domainnya. Kita dapat merasakan, satu ayat yang sama melahirkan derivasi makna dan keragaman interpretasi berbeda. Ahli gramatika menyorotinya dari sisi hubungan proposisional (khabari), dan darinya lahir konsep Ilmu Nahwu. Secara kesusasteraan, para ulama meneliti pola rhetoryc yang kemudian melahirkan konsep Ilmu Balaghah. Dan seterusnya, dan sebagainya. Lahir dari Kegelisahan Sebuah fakta menarik, bahwa Ilmu Nahwu adalah konsep ilmu tertua, jauh sebelum Ilmu Tafsir dan Hadits digagas. Ada peristiwa-peristiwa dialektika yang mendahului. Interaksi sosial orang Arab dan non-Arab, khususnya bangsa Persia, telah melunturkan kefasihan dalam bertutur. Banyak terjadi kesalahan gramatikal dan tentu hal tersebut menggelisahkan para ilmuwan Islam. Adalah Imam Ali bin Abi Thalib as, yang menyadari betapa pentingnya gagasan Ilmu yang mengatur tatagramatika, sehingga nilai-nilai esoteris bahasa Arab tetap lestari. Konon, dipanggillah Abu al-Aswad ad-Duali, lalu kepadanya ia mendiktekan beberapa konsep dasar. Kepada ad-Duali, Imam Ali berpesan; Unhu hadza an-Nahwa (Ikutilah jejak ini...). Sabda itulah yang kemudian menjadi prasasti nama untuk ilmu ini; Ilmu Nahwu. Kegelisahan Imam Ali adalah efek dari interaksi sosial dan akulturasi budaya antar-etnis, Arab dan non-Arab. Jauh di relung terdalamnya, bila kita melakukan sigi atas perkara ini, kita akan menemukan banyak hal yang saling berkelindan. Bahwa lahirnya Ilmu Nahwu bukan hanya soal ‘benar atau salah omong’. Lahirnya Ilmu Nahwu adalah gagasan melestarikan budaya, mengharumkan maruah, disamping membangun karakter. Sebab berbahasa yang baik adalah sebuah citra dari masyarakat beradab. Sebab bahasa yang baik adalah cermin dari pribadi manusia. Maka, mengubah manusia harus diubah dari caranya bertutur, caranya berkata-kata. Sebab bila diabaikan, kekacauan gramatika akan berbuntut terhadap bencana besar, yaitu gagalnya memahami al-Quran. Ini muaranya. Dari sini menjadi jelas, bahwa Imam Ali membangun masyarakat dimulai dari hulu, bukan hilir. Bukan hanya mengatur isim, fi’il atau huruf. Bukan hanya ngurusi syakal; dhummah, fathah, atau kasrah. Imam Ali memiliki kesadaran universal, bahwa titik tolak membangun karakter adalah mereformasi mental, dan hal itu dimulai dari bertutur yang baik. Lapisan dan Irisan Pada perkembangannya, Ilmu Nahwu kemudian melahirkan para pakar. Di lain sisi, ilmu Nahwu juga mengalami diversifikasi (pencabangan). Nahwu dibedakan dari Ilmu Shorrof, Balaghah, Bayan, Ma’ani dan Badi’. Terdapat belasan cabang ilmu, pada akhirnya. Nahwu pun hanya menjadi bagian darinya. Belakangan ilmu-ilmu tersebut dikenal dengan nama Qawa’id al-Lughah al-Arabiyah (Gramatika Bahasa Arab). Ibarat sebuah biji, Nahwu pada mulanya hanya memiliki lapisan luar-dalam, kulit-isi. Pada perkembangannya, ia melahirkan irisan. Nahwu sudah dibedakan dari pelbagai ilmu lainnya. Nahwu bukan lagi Shorrof, bukan Balaghah, Bayan atau Ma’ani. Realitas ini mengharuskan kita, para santri, untuk menyelami relungnya. Bukan hanya berenang di permukaannya. Ibarat mengarungi lautan, kita bukan hanya menjelajah keluasannya, namun juga menyelami kedalamannya. Sehingga, kekayaan laut yang dikandungnya¾minimal¾dapat diketahui, sebelum akhirnya dapat dieksplorasi. Sama seperti ilmu Nahwu, kita tidak boleh hanya berkutat memahami zhahir lafazh (redaksi eksternal). Kita harus menembus kedalamannya, sehingga pesan-pesan indah di dalamnya dapat kita fahami, sebelum akhirnya dapat diimplementasi. Sebab realitas bukanlah¾hanya¾sesuatu yang tampak. Realitas yang tampak hanyalah ‘bagian’, bukan ‘keseluruhan’. Manusia bukan hanya kulit, daging, tulang dan air. Sebab jika hanya itu, ia memiliki kesamaan dengan entitas binatang lain. Manusia adalah makhluk filosofis. Ia dinilai berdasarkan moral, ilmu, ketaqwaan dan hal-hal abstrak lain. Oleh karenanya, mengkaji sebuah ilmu, jangan pernah melepaskannya dari sisi filosofisnya, sebab itu adalah lapisan dalam yang harus diketahui. Ada adagium yang masih lekat di ingatan kita, serta selalu didengungkan oleh para guru kita di pesantren; Man tabahhara fi fannin, tabahhara ‘ala sairil funun (Sesiapa mempelajari secara komprehensif sebuah seni ilmu, ia seperti mempelajari ilmu seluruhnya). Terlepas dari benar-salah, kenyataan bahwa ada pola yang sama dalam setiap ilmu, meski secara lahiriah berbeda. Konon, ada seorang kyai sepuh yang dapat menjawab seluruh persoalan dengan Ilmu Nahwu. Dari cerita yang turun-temurun dikisahkan, suatu ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang hukum ‘Makan menggunakan Sendok’. Beliau dengan enteng menukilkan satu bait nazham di kitab Alfiyah ibnu Malik; “Wa fi ikhtiyarin la yaji’u al-Munfashil, idza taatta an yaji’a al-Muttashil (Dalam kondisi normal, tidak boleh menggunakan dhamir munfashil, jika masih memungkinkan penggunaan dhamir muttashil).” [1] Lalu Sang Kyai berkata; “Hukum makan dengan sendok tidak boleh, jika masih memungkinkan makan menggunakan tangan.” Penggalan kisah ini adalah buah dari perenungan lapisan dalam Ilmu Nahwu, bukan lapisan luarnya. Nahwu Teoritis-Filosofis Bilamana motivasi luhur yang melatarbelakangi gagasan Imam Ali bin Abi Thalib as adalah mereformasi manusia, maka Ilmu Nahwu harus difahami bukan hanya sebagai “Ilmu Dunia Kata”. Akan tetapi, Nahwu juga sebagai “Ilmu Dunia Nyata”. Sebagai sebuah konsep Ilmu, Nahwu adalah nilai universal dalam mengukur bahasa Arab. Ia harus diimplementasikan secara proporsional. Sehingga dari teori Nahwu, minimal melahirkan maharah dan kecakapan-kecakapan personal berbasis bahasa Arab. Pada tataran teoritis, ia meniscayakan tindakan praktis, yaitu tercapainya kemampuan membaca kitab yang mumpuni, kemampuan menulis bahasa Arab yang baik, juga keluasan dalam memaknai struktur bahasa Arab. Itu target minimalnya. Adapun pada tataran filosofis, Ilmu Nahwu harus dimaknai sebagai sebuah nilai universal untuk mengukur ‘Dunia Nyata’. Sebab dalam teori Nahwu, terkandung di dalamnya nilai-nilai luhur. Penikmat Ilmu Nahwu hanya tinggal menciduknya. Kemudian lebih penting mana, kulit atau isi? Teoritis atau filosofis? Keduanya sama-sama penting. Hanya yang perlu diperhatikan adalah tahapan-tahapannya. Jangan hanya melulu berkutat dengan teoritis, sementara mengabaikan pesan-pesan indah di dalamnya. Atau hanya bergairah menggali makna filosofis, sementara kemampuan baca kitabnya mbrodol. Nonsens. Idealnya, santri yang belajar Ilmu Nahwu mendapatkan dua-duanya. Ia cakap membaca kitab, juga beroleh nilai luhur yang dipancarkan tiap gagasan di dalamnya. Makna Filosofis Makna filosofis berarti memahami sesuatu berdasakan filsafat. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan segala sesuatu berdasarkan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukum-hukumnya.[2] Filsafat juga dimaknai sebagai sebuah pengetahuan berintikan logika, estetika dan metafisika. Ringkasnya, Filsafat memandang segala sesuatu berdasarkan nalar dan mengaitkannya dengan nilai-nilai universal. Maka dalam menciduk ‘makna filosofis’ dari tiap kaidah Nahwu, diperlukan nalar dan logika, yang darinya akan lahir berbagai nilai luhur dan luruh. Pemahaman teoritis sangat mengikat, namun makna filosofis tidak terbatas. Boleh jadi kita memahami konsep nahwu dari sisi yurisprudensi (hukum fikih), irfan dan tasawwuf, atau humaniora (sosial kemanusiaan). Yang penting, tiap nilai indah tersebut berpijak pada nalar yang sahih. Hal tersebut juga tercermin dari multiinterpretasi al-Quran oleh para ulama. Sebagian yang berkecenderungan estetis, seperti az-Zamakhsyari menulis tafsir dari sudut pandang estetika. Al-Quran dilihat dari kemahaindahan tekstualnya. Sebagian ulama yang memiliki kecenderungan historis, akan menulis tafsir berbasis kesejarahan. Sebagian lain ada ulama filosof, seperti Allamah Thabathaba’i, ia menulis tafsir berbasis filsafat. Ala kulli hal, setelah kita mengarungi lautan teoritis Ilmu Nahwu, menyelamlah sedalam mungkin! Di sana ada berjuta keindahan ‘Makna Filosofis’ yang tidak akan ditangkap oleh para pengarung, namun tak pernah menyelam.[] [1] Dhamir Muttashil adalah dhamir yang menempel pada kata sebelumnya, dan dhamir Munfashil adalah dhamir yang terpisah dari kata sebelumnya, atau dalam kalimat mandiri. [2] KBBI