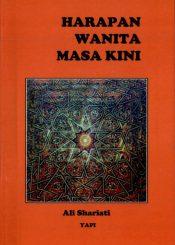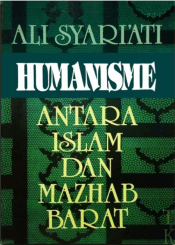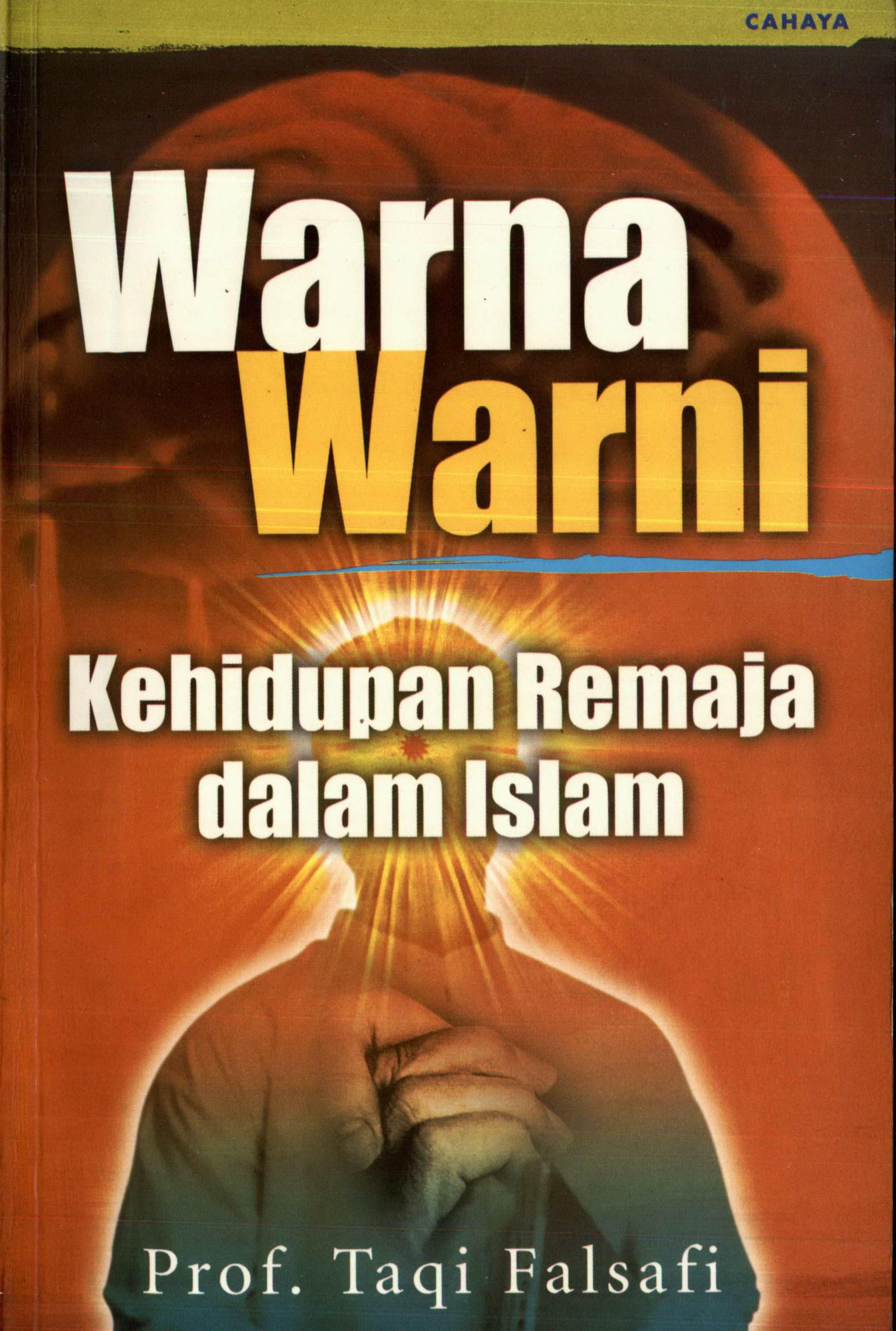Memperjungkan Wajah Islam Toleran dan Damai
Memperjungkan Wajah Islam Toleran dan Damai
Author :
Oleh Alamsyah M. Dja’far, Penulis Project Officer the Wahid Institute Jakarta
0 Vote
246 View
Sejak Orde Baru tumbang dan reformasi bergulir, Indonesia terus menghadapi sejumlah ancaman penting. Diantaranya, kekerasan dan melemahnya peran negara. The Wahid Institute lahir dalam situasi dan tantangan semacam itu. Berdiri pada 7 September 2004, lembaga ini ikut menyaksikan menguatnya “kepanikan” global mengenai ancaman terorisme global setelah Menara Kembar WTC di Amerika dirontokkan jaringan terorisme tiga tahun sebelumnya. Di saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi kasus-kasus kekerasan, khususnya berbasis etnis dan agama. Intoleransi yang digerakan kelompok berbasis agama bermunculan. Fenomena ini berkebalikan dengan keyakinan sebagai besa umat, Islam jelas menolak kekerasan dan terorisme. Toleransi yang ditopang kuat ajaran agama melalui proses sejarah yang panjang jelas telah mampu membentuk wajah agama yang moderat, bukan sebaliknya. KH. Abdurrahman Wahid, pendiri the Wahid Institute, menjadi salah satu orang yang berjuang meyakinkan publik Indonesia dan dunia mengenai prinsip Islam dan agama tersebut. Itu dilakukannya sejak tahun 80-an. Ia meyakinkan publik, agama bukan buldoser yang merusak budaya-budaya lokal; tak membenarkan kekerasan dan terorisme. Dan untuk itulah lembaga ini menetapkan visi ini: “memperjuangakan Islam moderat dan toleran”. Melalui jaringan pesantren, WI di masa-masa awal kehadirannya memulai upaya-upaya rekonsolidasi tokoh-tokoh moderat pesantren untuk menyuarakan tantangan kekerasan dan intoleransi. Gerakan ini diperluas dengan menghubungannya dengan jejaringan para aktivis NGO di sejumlah provinsi yang disebut gerakan Muslim Progresif. Bagi the Wahid Institute, muslim Indonesia memiliki perbedaan aktualisasi dengan muslim di tempat-tempat lain. Dalam perjalanan berikutnya WI membangun jaringan dengan kelompok antariman dan kelompok minoritas muslim. Di antaranya menggelar kelas-kelas Islamologi bagi calon pastur. Pengetahuan itu diharapkan menjadi bekal mereka untuk memahami doktrin dan khazanah Islam di Indonesia. WI juga mendiskusikan hal-hal penting dalam perbedaan tafsir menyangkut keislaman, misalnya terkait eksistensi Ahmadiyah. Kegiatan ini diikuti dengan kajian yang lebih struktural yang menyababkan kekerasan terhadap Ahmadiyah terjadi. Sejak 2008 hingga sekarang ini, WI berusaha mentradisikan pembuatan laporan-laporan pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi. Data-data itu diperoleh dari hasil kerjasama dengan mitra Lokal di Jawa, Sulsel, Ambon, dan NTB. Selain itu data juga diperoleh dari liputan media lokal dan nasional, cetak dan online. Ini cara untuk melihat seberapajauh kualitas jaminan kebebasan beragama di Indonesia, termasuk alarm bagi publik. Melalui laporan-laporan tersebut, WI mencatat kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi terus naik, terutama sejak lima tahun terakhir. Pada 2009, terdapat 121 peristiwa pelanggaran. Jumlah ini meningkat jadi 184 peristiwa tahun 2010, 267 peristiwa (2011), dan 278 peristiwa (2012). Tahun 2013, jumlahnya sedikit menurun jadi 245 peristiwa, tetapi kasusnya kian menyebar. Pelaku pelanggaran dibagi dua: negara dan non-negara. Termasuk dalam kategori non-negara ini adalah pelaku usaha. Laporan WI juga selalu mencatat dan mendata peraturan perundang-undangan terkait keagamaan di tingkat nasional dan lokal. Situasi ini berguna untuk melihat faktor-faktor pemicu lahirnya diskriminasi dan intoleransi. Tantangan Toleransi di Indonesia Dari data-data tersebut, jika diperas-peras masalah yang merusak dan mengancam pluralitas dan toleransi masyarakat hanya ada dua: faktor stuktural dan kultural. Keduanya juga saling terkait. Intoleransi yang terjadi di level kultural biasanya “didukung” oleh problem-problem strktural seperti pembiaran atau bahkan keterlibatan negara di dalamnya. Faktor struktural itu antara lain terkait dengan Peraturan Perundang-undangan mendukung prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme. Kapablitasi dan kapasitas birokrasi di dalam menjalankan konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya juga juga menjadi perkara penting. Visi dan keberanian pemimpin, baik di tingkat lokal dan nasional, juga hal penting lainya. Kami berpandangan, turunnya kasus-kasus pelanggaran di tahun 2013, kemungkinan disumbang sikap pemerintah yang saat itu mulai merespons dan mulai waspada. Respons dan kewaspadaan ini disumbang pula oleh banyaknya kritik dan kecaman atas kinerja pemerintah dalam kasus-kasus KBB, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Komunitas internasional juga mempertanyakan kasus-kasus yang menjadi sorotan dunia seperti Ahmadiyah, GKI Yasmin, Syiah, dan lain-lain. Misalnya suara-suara kritis dari Denmark, Jerman, Norwegia, di sidang sidang tinjauan periodik universal II (Universal Periodic Review - UPR) di Jenewa, Swiss 2012. Dalam beberapa kasus, aparat juga mulai bertindak profesional. Mereka serius menghadang penyerang terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Dalam banyak kasus, polisi justru mengevakuasi korban dengan alasan kalah jumlah dan menghindari bentrokan. Di level kultural, intoleransi terjadi lantaran menguatnya gerakan-gerakan intoleransi akibat globalisme. Salah satunya gerakan Wahabisme atau sering juga disebut salafisme. Salah satu cirinya adalah pandangan yang menolak demokrasi dan Pancasila serta tradisi takfir (pengkafiran) kepada mereka yang tidak sejalan dengan doktrin mereka. Sedang di sisi lain suara-suara kaum moderat dan kritis makin jarang didengar. Disayangkan pula ketidakmengertian masyarakat awam membuat sebagian mereka mendukung ide-ide kelompok salafi. Tidak sedikit, kekerasan dan intoleransi pada mulanya diangkat kelompok salafi lalu didukung oleh sebagian kalangan yang tak sehaluan dengan salafi seperti NU dan Muhammadiyah. Gus Dur menyebut ini sebagai “pembajakan” Islam agar mendulang dukungan di kalangan publik muslim lain. Meski begitu tentu harus diakui di tubuh kedua ormas tersebut kelompok-kelompok konservatif ikut mendesakan agenda mereka. Intoleransi dan kekerasan massa terhadap kelompok minoritas disumbang pula lemahnya penegakan hukum. Pelaku-pelaku kekerasan bermotif agama dihukum ringan. Lalu mereka belajar, jika massa pelakunya, dan isunya agama, hukumannya ringan. Beberapa Agenda Dalam perjalanannya, WI menilai ada beberapa langkah penting yang sedang dan hendak diperkuat dan dikembangkan. Pertama, mendorong kapasitas birokrasi dan kualitas layanan publik. Tentu saja WI tidak mengambil isu layanan publik secara umum. WI hanya mengambil isu yang terkait dengan isu agama dan keyakinan yang selama ini menjadi concern WI. Strategi dan pendekatan ini kami anggap sebagai salah satu cara ikut berkontribusi merespons problem struktural. Dalam kasus-kasus diskriminasi, tidak jarang aparat birokasi bias agama dan keyakinan dalam menjalankan layanan publik khususnya kepada minoritas. Padahal birokrasi sebagai aparatur sipil negara, seperti diatur dalam UU pasal 2 Nomor 5 Tahun 2014 tentng Aparatur Sipil Negara, harus memegang beberapa asas ini: kepastian hukum, profesionalitas, netralitas, non-diskriminasi, keadilan dan kesetaraan. Praktik ini bisa muncul dalam proses layanan IMB rumah ibadah, surat nikah di KUA dan Catatan Sipil, pembuatan KTP, dan lain-lain. Tahun ini, WI memulai kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi di Jawa Barat dan Blora di Kuningan. Kegiatan ini berusaha mengatasi bersama-sama kasus-kasus diskriminasi di bidang Administrasi Kependudukan. Untuk menopang ini, WI juga mengembangkan pemantauan berbasis seluler dan online. Publik diajak untuk melaporkan kasus-kasus diskriminasi via pesan singkat. Perbaikan layanan publik tentu saja sangat berkait dengan peraturan perundang-undangan. Ini basis pijakan birokrasi. Sayangnya masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memicu diskriminasi. Salah satunya UU PNPS 1965 dan UU Adminduk. Perbaikan kualitas layanan publik ini juga sangat bergantung pada “ideologi” negara melihat hubungan agama dan keyakinan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2015, Buku I dan II Prioritas Pembangunan Bidang, misalnya, bisa disimpulkan ada dua pendekatan dalam melihat isu keagamaan: “kerukunan” dan “kebebasan”. RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode setahun. Dokumen itu bentuk dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter termasuk prioritas pembangunan. “Kerukunan” tampaknya lebih menekankan aspek stabilitas dan bersifat atas bawah sebagaimana ditunjukan di masa Orde Baru. Sedang “kebebasan” lebih menekankan aspek hak dasar individu dan bersifat dari bawah ke atas. Mereka yang tak setuju konsep kerukunan beranggapan, masyarakat tak perlu dirukun-rukunkan. Yang perlu adalah jaminan dan kepastian bahwa setiap orang bisa menjalankan agama sesuai agama dan kepercayaan. Kedua, memperkuat Islam moderat. Dianugrahi jaringan pesantren yang luas, WI berusaha memperbesar jaringan dan dukungan dari lingkungan peantren seperti santri dan tokoh-tokoh Nahdliyin. Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, memiliki potensi besar yang bisa menyumbang bagi perdamaian di internal Islam dan antarumat beragama. Salah satu yang terus ingin diperkuat adalah jaringan “kiai kampung” yang sudah diinisiasi Gus Dur. DI antara program yang menyasar pesantren adalah training penulisan bagi santri, penyusunan kurikulum toleransi, dan lain-lain. WI juga tengah berusaha menyasar publik umum untuk mendukung ide-ide toleransi, termasuk di kalangan pesohor dan profesional. Upaya ini salah satunya diwujudkan melalui perayaan International Peace of Day yang melibatkan lebih dari 1000 orang. Para pesohor juga terlibat di dalamnya. Mereka-mereka ini bisa menjadi pendukung aktif gerakan toleransi jika dirawat dengan maksimal. Ketiga, menciptakan pemimpin-pemimpian muda di lingkungan pelajar dan anak-anak muda. Belakangan ini, intoleransi menjangkiti anak-anak muda, khususnya pelajar. Misalnya hasil survei yang dirilis Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian tahun 2012. Hampir lebih dari 40% pelajar di Jabodetabek mendukung ide dan aksi-aksi kelompok radikal. Tantangan ini makin nyata seiring dengan “bonus demografi” yang dimulai pada 2015. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Pada tahun 2010, proporsi penduduk usia produktif (15-65 tahun) sebesar 66,5 persen. Proporsi ini terus meningkat mencapai 68,1 persen pada tahun 2028 sampai tahun 2031. Jika umpanya 10 % saja dari usia produktif, khususnya remaja, dijangkiti virus intoleransi dan radikalisme, kita akan menghadapi perkara serius. Untuk bidang ini WI mengembangkan sejumlah kegiatan yang pernah dimulai sejak 2010. Yakni training toleransi dan perdamaian di sekolah-sekolah. Kami mengembangkan Peace Ambassador. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 700 pelajar di sejumlah provinsi. Tahun ini WI mengembangkan Papan Permainan Neger kompak yang sudah dilatih lebih dari 400 pelajar di Jabodebak. Negeri Kompak mrupakan peraminan mirip monopoli berisi nilai dan karakter positif seperti toleransi dan anti perdamaian. Keempat, penguatan ekonomi. WI percaya bahwa penguatan toleransi dan perdamaian bukan isu tunggal. Ia terkait dengan aspek-aspek lain. Salah satunya ekonomi. Tidak sedikit kasus intoleransi terjadi karena dipicu faktor ekonomi dan pengetahuan. Karena itu sejak satu-dua tahun lalu, WI mengembangkan program penguatan ekonomi. Salah satu yag dikembangkan penguatan ekonomi masjlis taklim. Lebih dari 500 anggota majlis taklim di Sukabumi, Bandung, dan Garut dilatih mengenai BMT dan pengelolaan ekonomi. Kegiatan ini bekerjasama dengan SAPA (Strategic Alliance for Poverty Alleviation), jaringan pengentasan kemiskinan yang terdiri dari puluhan organisasi dan bekerjasama dengan sejumlah pemerintah lokal. Di Depok dan Bogor WI mengembangkan aktivitas simpan pinjam. Anggotanya kini sudah lebih dari 300 ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan ini selain mendpat pinjaman dana antara Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta, mereka juga terlibat dalam obrolan-obrolan ringan seputar toleransi dan perdamaian. Melalui sejumlah pendekatan dan aktivitas di atas, kami berharap penguatan toleransi dan perdamaian bisa menjadi gerakan arus utama di Indonesia. Semoga! [1] Disajikan dalam Regional Conference on “Strengthening Accountability for Violations of Religious Freedom in Southeast Asia”, Panel 1 “Understanding and promoting religious tolerance and pluralism in society: Best practices,” National Library-Jakarta, 18 November 2014