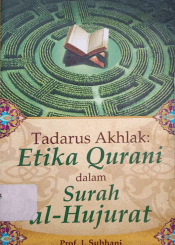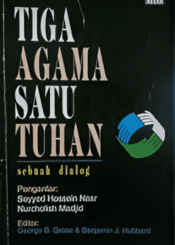Non-Muslim Identik dengan Kafir?
Non-Muslim Identik dengan Kafir?
Author :
Islamindonesia
0 Vote
211 View
Pemimpin non muslim
Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi walî dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (Al-Nisa’: 114). Di dalam ayat lain Allah bahkan melarang menjadikan kerabat kita sebagai awliyâ’—ketika mereka lebih memprioritaskan kekafiran atas keimanan (Al-Taubah: 23). Sebagian kalangan—berdasarkan ayat di atas dan ayat-ayat serupa lainnya—menyimpulkan bahwa, haram bagi umat Islam mengangkat pemimpin non-Muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim dianggap sebagai penyangkalan terhadap perintah suci Allah, dan sekaligus merupakan ketundukan terhadap pemerintahan thâghût. Maka, dalam momentum pileg dan pilpres seperti tahun 2014 ini, isu kepemimpinan non-Muslim kembali digulirkan. Berseliweran kampanye atas nama agama untuk menolak kepemimpinan non-Muslim. Lepas dari hak semua orang untuk dipilih dalam negeri demokratis seperti Indonesia, pengantar pendek ini berupaya membuka diskusi mengenai hal krusial dalam kehidupan ketatanegaraan kita – seungguhnya juga kehidupan keberagamaan dalam negeri yang plural seperti Indonesia – dengan menawarkan argumentasi yang berbeda mengenai hal ini. Dengan mengasumsikan kesepakatan bahwa kata walî di sini bermakna pemimpin, pengantar sederhana ini ingin sekali lagi mengajukan jawaban terhadap pertanyaan : benarkah kafir—pelaku kekafiran— identik dengan non-Muslim? Apakah non-Muslim serta-merta berarti kafir?[1] Kufr adalah penyangkalan terhadap kebenaran Kata kafir dalam bahasa Arab (lihat al-Munjid, misalnya) berasal dari kata ka-fa-ra yang berarti ‘menutupi’. Di dalam Al-Quran, misalnya, petani disebut kuffâr (orang-orang “kafir”) karena mereka menggali tanah, menanam bebijian, lalu menutupnya kembali dengan urukan tanah (Al-Hadid: 20). Kata ini pula yang kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kekafiran, dengan demikian, adalah pengingkaran dan penyangkalan atas kebenaran yang memang telah dipahami, diterima, dan diyakini oleh seseorang sebagai sebuah kebenaran. Orang kafir adalah orang yang, karena berbagai alasan (vested interest) menyangkal atau bersikap tidak konsisten dalam mengikuti kebenaran yang diyakininya. Jika seseorang tidak percaya kepada kebenaran tertentu, dalam hal ini kebenaran Islam, maka apa yang ia tutupi? Apa yang ia sangkal? Jika ini yang jadi ukuran, maka non-Muslim yang tak percaya akan kebenaran Islam bukanlah kafir. Di bawah ini uraiannya. Di dalam Al-Quran, kekafiran identik dengan tindakan penyangkalan secara sadar, tanpa pengaruh tekanan dari luar. Iblis dan Fir’aun, misalnya, disebut kafir karena adanya penolakan dan penyangkalan terhadap kebenaran yang bahkan diyakini oleh keduanya (abâ wa-stakbara). Dengan demikian, kekafiran mengandaikan adanya penolakan dan pengingkaran seseorang atas sebuah kebenaran yang sampai kepadanya, yang telah ia pahami dan yakini sebagai sebuah kebenaran. ”Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.” (Al-Baqarah:89). Maka, jika seseorang tidak menerima Islam, karena ketidak-tahuan, atau karena argumen-argumen tentang Islam yang sampai kepadanya tidak meyakinkannya, apakah orang-orang seperti ini dapat disebut kafir. Karena itu, baik para ulama salaf dan khalaf (belakangan), berpendapat adanya kaharusan pemilikan pengetahuan, yakni pengetahuan yang benar dan meyakinkan, sebelum seseorang dikategorikan sebagai kafir ketika mengingkarinya. Juga jika seseorang menolak Islam karena kesombongan, padahal sudah terang baginya kebenaran Islam, jelas penolakan ini adalah sebentuk kekafiran. Imam Ja’far Shadiq berkata: “Sekelompok orang tidaklah kafir bila mereka tidak tahu (jahil), diam dan tidak menentang.” Imam Ghazali juga mengutarakan pandangan serupa. Menurutnya, orang-orang non-Muslim yang tidak sampai kepadanya dakwah tidak dapat disebut sebagai kafir. Kategori ini dipahami sebagai orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam, atau Islam tak sampai kepada mereka dalam bentuk yang membuat mereka yakin. Kata beliau: “Orang-orang yang sampai dakwah kepada mereka, namun kabar-kabar yang mereka terima adalah kabar-kabar yang tidak benar—membuat citra Islam menjadi buruk—atau yang mengalami pemalsuan sedemikian rupa, maka orang-orang seperti ini masih diharapkan bisa masuk surga.” Bahkan, Ibn Taymiyah dalam Majmu’ Fatawa-nya berpendapat, seseorang tidak dapat dikafirkan sampai tegak kepadanya hujjah (argumentasi yang meyakinkan). Sebab, boleh jadi orang tersebut belum mendengar nash-nash, atau sudah mendengarnya namun tidak sahih, atau adanya dalil lain yang membuatnya harus melakukan takwil—betapapun takwilnya ini keliru. Demikian pula pendapat Imam Syafi’i dan yang lain. Termasuk juga ‘alim kontemporer seperti Syaikh Mahmud Syaltut (dalam Al-Islâm ‘Aqîdah wa Syarî’ah-nya). Dari argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan, menurut penulis, mudah difahami bahwa kriteria ini seharusnya tidak diterapkan hanya kepada Muslim yang melakukan tindak kekufuran, melainkan juga kepada non-Muslim yang tidak memeluk Islam karena belum sampai dakwah dan/atau informasi tentang Islam yang sampai kepadanya tidak membuatnya yakin akan kebenaran Islam. Berdasar argumentasi di atas, maka non-Muslim yang tulus dalam memilih dan meyakini keyakinannya tidak serta-merta dapat disebut kafir, yakni menutupi keyakinannya akan kebenaran. (Murtadha Muthahhari dalam Keadilan Ilahi, menyebut orang-orang non-Muslim seperti ini sebagai orang-orang Muslim Fitri (muslimûn bil-fithrah). Yakni orang-orang yang secara nominal bukan Muslim, tetapi ada hakikatnya berserah-diri (aslama) kepada kebenaran (Tuhan). Kekafiran: Kategori Moral, Bukan Teologis Jika kita teliti teks-teks Al-Quran dan Hadis, kita mendapatkan kesan kuat bahwa pada puncaknya kekafiran itu kategori moral, bukan kategori teologis. Imam ‘Ali pernah mengatakan: “Ada orang beragama tetapi tidak berakhlak, dan ada orang yang berakhlak tapi tidak bertuhan.” Pernyataan Imam ‘Ali ini bisa dilihat sebagai semacam sindiran, bahwa orang beragama, alih-alih dapat disebut sebagai orang baik atau saleh, justru lebih tepat dikategorikan kafir. Bukankah dari keimanan—sebagai jantung keberagamaan—harusnya lahir tindakan-tindakan kebaikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral universal? Dapatkah disebut beriman, ketika tindakan-tindakannya bahkan berseberangan dari prinsip-prinsip kebaikan? Nabi Saw bersabda: “Tidak termasuk orang yang beriman, siapa saja yang kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar.” (HR. Bukhari) Dalam sebuah hadis terkenal, Nabi Saw bersabda: “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri.” (HR. Bukhari). Dalam sabda-sabda Nabi Saw di atas, keimanan secara tegas dipertautkan dengan kesadaran dan kepedulian sosial. Keimanan bukan semata keyakinan yang terpendam di dalam hati. Sikap acuh dan “masa bodoh” terhadap kesusahan orang lain atau pun pelanggaran terhadap syariat secara tegas dinyatakan sebagai “tidak beriman”, yakni kekafiran terselubung. Demikian pula dalam ibadah mah-dhah. Shalat, misalnya, alih-alih mengundang pujian Allah, justru sebaliknya Allah sebut sebagai tindakan mendustakan agama jika tak diikuti dengan kesadaran dan empati sosial yang riil. “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Al-Ma’un: 1-7). Bukankah “mendustakan” agama adalah esensi kekafiran itu sendiri? Masih berhubungan dengan pengidentikan keimanan dengan empati sosial, dalam hadis yang lain Nabi Saw bersabda: “Tak beriman seseorang dari kalian hingga dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri.” Tentang Kristen dan Trinitas Boleh jadi ada yang masih merasakan kemusykilan. Jika non-Muslim memang tak identik dengan kafir, dan kekafiran adalah kategori moral, lalu bagaimana memahami firman Allah: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa.” (Al-Ma’idah: 73)? Ada beberapa kemungkinan penafsiran atas ayat ini. Pertama, bahwa yang dikafirkan adalah orang-orang yang mengada-adakan Trinitas yang sesungguhnya tak diajarkan Yesus. Pada kenyataannya, sebagian kaum Nasrani mempercayai adanya Pauline Christianity (Kristen model Rasul Paulus yang dipercayai memperkenalkan Trinitas), Judeo Christianity (Kekristenan yang asli dan tak mengandung Trinitas). Artinya, yang disebut sebagai “telah kafir” dalam al-Qur’an adalah orang-orang yang secara sengaja mengadakan bid’ah Trinitas – sebagai kemusyrikan – dan bukan para penganut agama Nasrani yang memang mempercayainya dengan tulus sebagai sebuah kebenaran. Kemungkinan tafsir lain adalah, yang dimaksud Al-Quran itu bukan Trinitas sebagaimana yang diyakini kaum Nasrani, tapi Triteisme. Yang pertama tetap merupakan tauhid. Yakni, tiga dalam satu (unitas). (Yang dua adalah semacam tajalliy-Nya, jika mengikuti pandangan ‘irfan). Berdasar hal ini, yang bisa disebut kafir adalah penganut Triteisme ini, yang tak merupakan mayoritas kaum Nasrani sekarang. Pemimpin Non-muslim? Dari uraian singkat di atas, sesungguhnya larangan Allah untuk mengangkat walî yang kafir, tidak serta-merta berlaku atas pemimpin non-Muslim. Yang terlarang adalah mengangkat pemimpin yang jahat, yang merugikan dan mengabaikan kemaslahatan rakyat demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Dengan kata lain, lebih mementingkan “kekafiran”-nya (despotisme, korupsi, kesewenangan, dsb.) atas “keimanan” (kesejahteraan, rasa aman, kemaslahatan bersama), baik dia Muslim maupun non-Muslim. Dalam buku ini, Muhsin Labib telah menunjukkan dengan baik bentuk-bentuk dan kriteria keimanan dan kekafiran dalam konteks monoteisme universal. Soal kepemimpinan non-muslim, Anda akan temukan banyak uraian dan bahan-bahan menarik dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini adalah sebuah upaya yang sangat penting untuk mendiskusikan secara terbuka isu penting yang cukup sensitif dan kontroversial ini. Khususnya, karena belakangan ini muncul dan menguat kecenderungan kepada eksklusivisme Islam yang luar biasa. Jika tidak disajikan penafsiran yang berbeda, kecenderungan eksklusivstik ini bisa mendapatkan bentuknya yang sangat ekstrem, hingga berkeyakinan bahwa non-Muslim – bahkan Muslim yang tak sejalan dengan mereka — tak punya hak hidup di bumi Allah ini. Fenomena ISIS merupakan bukti hidup tentang hal ini. Sudah tentu kami yakin tak semua orang akan punya pendapat yang sama dengan penulis buku, dan kata pengantar, ini (saya pun tak pernah menganggap pendapat saya sebagai final, apalagi sebagai satu-satunya kebenaran). Tapi—kalaupun tak sependapat—diharapkan setidaknya (sebagian) pembaca akan memberikan benefits of the doubt dengan mendapati adanya kemungkinan penafsiran berbeda tentang soal ini. Hal ini diharapkan akan setidaknya melahirkan pandangan yang lebih toleran terhadap non-Muslim dan hak-haknya. Juga membuka kesempatan bagi diskusi-diskusi lebih jauh mengenai isu ini, dan isu-isu lain mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim. Tahniah bagi Sdr. Muhsin Labib. Wa-Allahu a’lam