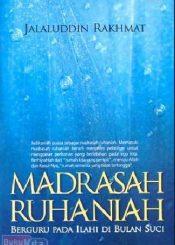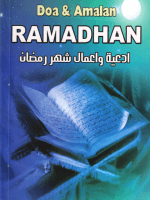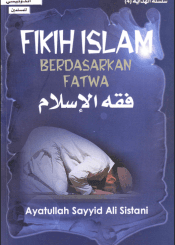HUKUM-HUKUM TAKLID
HUKUM-HUKUM TAKLID
0 Vote
1186 View
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas nabi dan nabi termulia, Muhammad dan keluarga beliau yang suci. Dan semoga laknat abadi selalu terlimpahkan atas musuh-musuh mereka semua dari sejak sekarang hingga hari kiamat. BAB 1 HUKUM-HUKUM TAKLID Masalah 1: Akidah seorang muslim tentang Ushuluddin harus berdasarkan kepada pengetahuan dan keyakinan (bashirah), dan ia tidak boleh bertaklid berkenaan dengan hal ini. Artinya, tidak boleh ia menerima ucapan orang lain yang memiliki pengetahuan tentang Ushuluddin tersebut hanya dengan alasan bahwa ia mengatakan demikian. Akan tetapi, jika ia meyakini akidah-akidah Islam yang benar dan menampakkannya—meskipun keyakinannya itu tidak berdasarkan pada bashirah tersebut, maka ia adalah muslim dan mukmin, dan seluruh hukum Islam dan iman berlaku atasnya. Adapun berkenaan dengan hukum-hukum (amaliah praktis sehari-hari)—selain hukum-hukum yang bersifat dharuri dan pasti—seseorang harus menjadi mujtahid—yang bisa menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya, bertaklid kepada seorang mujtahid, atau mengerjakan kewajiban dan tugasnya atas dasar ihtiyath sehingga ia yakin telah melaksanakan kewajibannya. Misal, jika sebagian mujtahid berfatwa bahwa sebuah amal adalah haram, sementara itu sebagian mujtahid yang lain menyatakan bahwa amal tersebut tidak haram, maka hendaknya ia tidak melakukannya, dan jika sebagian mujtahid menyatakan bahwa sebuah amal adalah wajib, sementara itu sebagian mujtahid yang lain menegaskan bahwa amal tersebut adalah sunah, maka hendaknya ia mengerjakan amal tersebut. Masalah 2: Taklid dalam hukum (Fiqih) adalah mengamalkan (sebuah hukum) sesuai dengan ketentuan dan pendapat seorang mujtahid. Kita hanya boleh bertaklid kepada seorang mujtahid yang (memenuhi syarat-syarat berikut ini): a. Laki-laki. b. Balig. c. Berakal. d. Bermazhab Syi'ah Itsna 'Asyariyah. e. Anak halal. f. Hidup. g. Adil. Orang yang adil adalah orang yang mengerjakan setiap kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang telah diharamkan atasnya. Tanda keadilan seseorang adalah, bahwa secara lahiriah, ia adalah seorang yang baik sehingga apabila kita menanyakan tentang dia kepada penduduk setempat, tetangga, atau orang-orang yang bergaul dengannya, mereka akan membenarkan bahwa ia adalah orang yang baik. Jika perbedaan fatwa antar para mujtahid berkenaan dengan masalah-masalah yang sering dialami oleh setiap mukallaf sehari-hari diketahui—walaupun secara global, maka mujtahid yang kita taklidi haruslah mujtahid yang a'lam. Yaitu, ia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan para mujtahid lain yang hidup semasa dengannya dalam memahami hukum-hukum Allah. Masalah 3: Kita dapat mengenal seorang mujtahid dan mujtahid yang a'lam melalui tiga jalan berikut ini: Pertama, kita sendiri yakin (bahwa ia adalah seorang mujtahid atau a'lam), seperti kita sendiri adalah seorang ulama dan dapat mengenali seorang mujtahid dan mujtahid yang a'lam. Kedua, dua orang alim dan adil yang dapat menentukan seorang mujtahid yang a'lam membenarkan kemujtahidan atau ke-a'lam-an seseorang, dengan syarat dua orang alim dan adil yang lain tidak menentang ucapan mereka tersebut. Bahkan menurut pendapat yang zhahir, kemujtahidan atau ke-a'lam-an seseorang dapat dibuktikan melalui ucapan satu orang yang menjadi kepercayaan kita. Ketiga, kita dapat memperoleh kemantapan hati atas kemujtahidan atau ke-a'lam-an seseorang melalui cara-cara yang 'uqala'i (yaitu, masuk akal menurut pandangan orang-orang yang berakal—pen.). Seperti, beberapa orang ulama—yang dapat menentukan seorang mujtahid atau mujtahid yang a'lam dan ucapan mereka menyebabkan kita memperoleh kemantapan hati—membenarkan kemujtahidan atau ke-a'lam-an seseorang. Masalah 4: Jika perbedaan fatwa antara dua orang mujtahid atau lebih berkenaan dengan masalah-masalah yang sering dialami oleh mukallaf sehari-hari diketahui—walaupun secara global—dan juga diketahui bahwa salah seorang dari mereka adalah a'lam dibandingkan dengan yang lainnya, akan tetapi sulit bagi kita untuk menentukan (siapakah) mujtahid yang a'lam (di antara mereka itu), maka yang ahwath adalah kita ber-ihtiyath—apabila memungkinkan—dalam semua fatwa berkenaan dengan masalah-masalah tersebut, (meskipun dalam masalah ini terdapat perincian pembahasan dan kesempatan ini tidak cukup untuk memaparkan seluruhnya). Apabila tidak mungkin bagi kita untuk ber-ihtiyath, seluruh amalan kita harus sesuai dengan fatwa marja' yang kemungkinan ke-a'lam-annya melebihi marja'-marja' yang lain. Dan jika kemungkinan ke-a'lam-an kedua marja' tersebut adalah sama, maka kita berhak memilih antara keduanya. Masalah 5: Fatwa seorang mujtahid dapat diperoleh melalui empat jalan: Pertama, mendengar dari mujtahid itu sendiri. Kedua, mendengar dari dua orang adil yang menukil fatwa mujtahid tersebut. Ketiga, mendengar dari seseorang yang hati kita merasa mantap dengan ucapannya. Keempat, melihat (baca: membaca) buku tuntunan amaliah praktis mujtahid tersebut, asalkan hati kita mantap dengan kebenaran buku tersebut. Masalah 6: Selama kita tidak yakin bahwa fatwa mujtahid berubah, kita masih bisa mengamalkan seluruh fatwa yang tertulis di dalam buku tuntunan amaliah praktisnya. Jika kita memberikan kemungkinan bahwa fatwanya telah berubah, tidak wajib kita menelitinya. Masalah 7: Jika seorang mujtahid mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah, maka orang yang bertaklid kepadanya tidak boleh mengamalkan fatwa mujtahid lain berkenaan masalah tersebut. Akan tetapi, jika ia tidak mengeluarkan fatwa dan hanya berkata, "Ihtiyath adalah begini dan begitu," seperti ia berkata, "Ihtiyath adalah dalam rakaat pertama dan kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, mushalli harus membaca satu surah lagi secara sempurna," maka ia dapat mengamalkan ihtiyath tersebut—ihtiyath ini dinamakan ihtiyath wajib—atau merujuk kepada fatwa mujtahid lain yang diperbolehkan untuk ditaklidi. Dengan demikian, apabila mujtahid yang lain ini berfatwa cukup hanya membaca surah Al-Fatihah (dalam kedua rakaat tersebut), maka ia boleh tidak membaca surah yang lain. Begitu juga hukumnya jika seorang mujtahid yang a'lam berkata, "Masalah ini masih perlu direnungkan (mahallu ta'ammul) atau isykal (mahallu isykal)." Masalah 8: Jika mujtahid a'lam ber-ihtiyath setelah atau sebelum mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah, seperti ia berkata, "Bejana najis menjadi suci setelah dicuci di dalam air kur sebanyak sekali, meskipun yang ihtiyath adalah hendaknya bejana itu dicuci sebanyak tiga kali," maka orang yang bertaklid kepadanya dapat meninggalkan ihtiyath tersebut. Ihtiyath semacam ini dinamakan ihtiyath mustahab. Masalah 9: Jika mujtahid yang kita taklidi meninggal dunia, hukum mujtahid tersebut setelah meninggal dunia adalah sama dengan hukumnya pada saat ia masih hidup. Atas dasar ini, jika ia adalah a'lam dibandingkan dengan mujtahid yang masih hidup, maka kita—asalkan kita tahu (fatwanya) berbeda (dengan fatwa mujtahid yang masih hidup) berkenaan dengan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari walaupun secara global—harus tetap bertaklid kepadanya, dan jika mujtahid yang masih hidup adalah a'lam darinya, maka kita harus merujuk kepada mujtahid yang masih hidup tersebut. Apabila tidak diketahui manakah di antara kedua mujtahid tersebut yang a'lam atau mereka adalah sama-sama a'lam, maka kita memiliki pilihan untuk menyesuaikan amalan kita dengan fatwa mujtahid yang mana saja, kecuali berkenaan dengan masalah ilmu ijmali atau adanya sebuah hujjah ijmali atas suatu taklif, seperti perbedaan fatwa tentang masalah kewajiban mengqashar dan menyempurnakan (shalat). Dalam masalah-masalah seperti, kita harus memperhatikan kedua fatwa tersebut. Maksud dari "taklid" di permulaan masalah ini adalah sekadar keyakinan kuat untuk mengikuti fatwa seorang mujtahid tertentu, bukan mengamalkan fatwa-fatwanya secara praktis. Masalah 10: Jika kita mengamalkan fatwa seorang mujtahid berkenaan dengan suatu masalah dan setelah ia meninggal dunia, sesuai dengan tugas yang kita miliki, kita mengamalkan fatwa mujtahid yang masih hidup berkenaan dengan masalah yang sama, maka—untuk kedua kalinya—kita kita tidak boleh mengamalkan masalah tersebut sesuai dengan fatwa mujtahid yang sudah meninggal dunia itu. Masalah 11: Kita wajib mempelajari masalah-masalah yang—pada umumnya—kita membutuhkannya. Masalah 12: Jika kita menghadapi sebuah masalah yang kita tidak mengetahui hukumnya, maka kita harus ber-ihtiyath atau bertaklid sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Akan tetapi, jika kita tidak mendapatkan fatwa mujtahid yang a'lam berkenaan dengan masalah tersebut—meskipun secara global kita tahu bahwa mujtahid non-a'lam memiliki fatwa yang berbeda dengan fatwa mujtahid a'lam dalam masalah ini, maka diperbolehkan kita bertaklid kepada mujtahid non-a'lam. Hanya saja, tetap kita harus memperhatikan urutan mujtahid yang a'lam setelah itu. Masalah 13: Jika kita menginformasikan fatwa seorang mujtahid kepada seseorang dan fatwa mujtahid tersebut berubah, maka kita tidak wajib memberitahukan kepadanya bahwa fatwanya telah berubah. Akan tetapi, jika kita tahu—setelah menginformasikan fatwa—bahwa kita telah keliru dalam menginformasikannya dan informasi kita itu dapat menyebabkan ia beramal tidak sesuai dengan kewajiban syar'i-nya, maka berdasarkan ihtiyath wajib kita harus membenarkan kekeliruan tersebut, apabila memungkinkan. Masalah 14: Jika seorang mukallaf mengerjakan amalan-amalannya tanpa bertaklid selama beberapa waktu, lalu ia bertaklid kepada seorang mujtahid, dalam hal ini apabila mujtahid tersebut menghukumi bahwa seluruh amalannya itu adalah sah, maka seluruh amalan tersebut adalah sah. Apabila mujtahid itu tidak menghukumi demikian, akan tetapi mukallaf tersebut tidak tahu hukum lantaran ia adalah jahil qashir dan kebatalan seluruh amalan tersebut tidak disebabkan oleh masalah-masalah rukun dan semisalnya, maka seluruh amalannya adalah sah. Begitu juga sah seluruh amalannya, meskipun ia tidak tahu hukum lantaran ia adalah jahil muqashshir, akan tetapi kebatalan amalannya itu disebabkan oleh suatu hal yang seandainya tidak dilakukan lantaran ia tidak tahu, maka amalan tersebut masih dihukumi sah, seperti masalah membaca bacaan shalat dengan suara keras pada kondisi yang semestinya harus dibaca pelan, atau sebaliknya. Begitu juga sah amalannya jika ia tidak mengetahui bagaimana tata cara ia telah mengerjakan seluruh amalannya yang lalu itu, kecuali dalam beberapa kondisi yang telah dipaparkan dalam buku risalah amaliah praktis Al-Minhaj. http://www.alhassanain.com