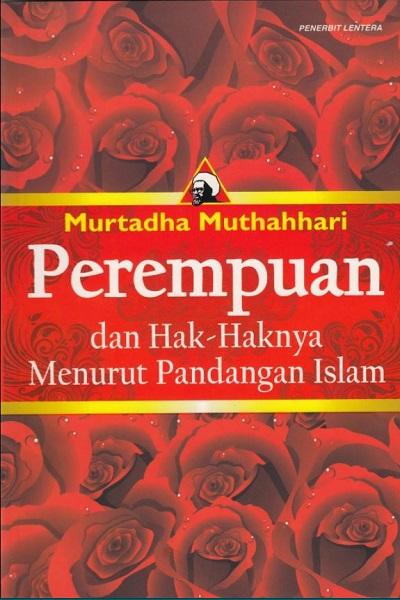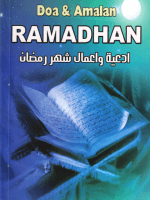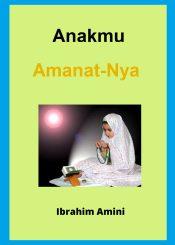Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya. Manusia yang mencapai derajat muttaqin akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allāh, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah daripada pria.1
Salah satu hal yang dikomentari al-Qur‟ān ialah masalah penciptaan pria dan wanita. Al-Qur‟ān tidak berdiam diri dalam hal ini, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk seenaknya mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, lalu menuduh Islam meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri. Islam telah meletakkan pandangannya mengenai wanita.
Dalam al-Qur‟ān tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lain: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.2
Al-Qur‟ān mengandung banyak kisah dan cerita tentang wanita baik peranannya ataukepahlawanannya atau sebagai istri dari Nabi dan Rasul yang mendampingi dan membantu tugas suami dengan penuh ketentuan.3 Dengan cara demikian al-Qur‟ān menolak konsep yang tersiar pada masa itu dan yang hingga kini masih tetap ada di kalangan tertentu dan bangsa tertentu di dunia. Dan dengan cara itulah al-Qur‟ān membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, sebagai makhluk separuh iblis.4
Selain itu, al-Qur‟ān al-Karīm membebankan tanggung jawab kepada pria dan wanita untuk membimbing dan mempebaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan di dalam firman
Allāh:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم
Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allāh dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh; Sesungguhnya Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [09]: 71)5
Ketika seorang wanita meniti karier, di mana karier tersebut adalah sebuah pekerjaan yang ikut menyumbang kemaslahatan umat tentunya ia menjadi bagian dari bangunan Islam itu.6
Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menjelaskan persoalan ini.
Artinya: Dari Aisyat r.a. dan Nabi saw, mengatakan: kalian (istri-istri Nabi) sungguh telah diizinkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. (HR. Bukhāry)7
Dalam hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad disebutkan bahwa „Umar melarang para istri Nabi keluar rumah. Saat itu „Umar tetap dapat mengenali Saudah (istri Nabi) yang keluar saat isya‟. Namun kemudian dijelaskan, mereka boleh keluar karena ada keperluan penting. Hal ini menunjukkan keluar rumah bagi wanita bukan larangan yang bersifat mutlak, tetapi dibolehkan jika ada keperluan penting mendesak atau darurat.
Islam juga telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban pria, bukan kewajiban wanita. Tetapi jika ia berkehandak, maka diperbolehkan seorang wanita untuk bekerja, jika diijinkan oleh suaminya atau ayahnya jika ia belum menikah, sebab hal itu mubah baginya.
Benar bahwa pekerjaan wanita di rumah, mengurus anak- anak dan suami, adalah pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Wanita adalah pemilik rumah dan tuan dari “kerajaan kecil ini”. Pekerjaan ini tidak dapat dinilai dengan apapun. Adapun dalam pekerjaan yang dapat memberikan
penghidupan, pekerjaan yang bernilai ekonomis, pekerjaan yang menjadi sumber rezeki, hendaknya wanita memilih pekerjaan yang mampu dia lakukan saja.8
Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah digariskan syariat Islam. Seorang Muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria.9
Hanya saja, perlu diperhatikan, bahwa wanita bolehbekerja dengan cacatan:
- Tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu.
- Mendapatkan izin dari suami.
3.Tidak bekerja di tempat yang lelaki dan wanita saling berbaur.
- Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian Muslimah.
- Senantiasa menjaga aurat dan kesucian diri.10
Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua kutub yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan bahwa wanita harus di dalam rumah, dan tidak boleh berperan di ranah publik. Pandangan lain menyatakan wanita mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut terjadi karena belum dipahaminya konsep tentang hak-hak wanita secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur‟ān masih bias jender.11
Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia profesi (karier) yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai
ra’iyah fī baity zawjihā (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendikiawan Muslim.12
Mengacu pada surat al-Ahzab ayat 33:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ
Artinya:
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.13
Sayyid Quthb menulis bahwa
waqarna berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, tulisannya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini
mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.”14 Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, dan wanita sebagai wanita, namun selanjutnya ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai inheren.15
Selanjutnya beliau juga mengungkapkan ketika berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan wanita, sistem tersebut menyimpulkan perbedaan itu sebagai indikasi dari nilai-nilai yang berbeda juga. Tidak ada indikasi bahwa al-Qur‟ān menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu, apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren kalau sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya. Masalah timbul ketika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan ini terjadi.16
Dalam
tafsīr al-Marāghī dijelaskan bahwa kata qarana berasal dari kata “qorro, yaqorru” adapun asalnya adalah “iqrorna”, namun alifnya dibuang yang berarti “tetaplah kamu sekalian”.17
Menurut al-Qurthuby (w. 761 H) yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam
Wawasan Al-Qur’ānnya bahwa, makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah, walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi tetapi selain mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya al- Qurthuby menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali karena keadaan darurat.18
Quraish Shihab juga menyadur dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam bukunya
“Ma’rakah al-Taqallid” bahwa itu bukan berarti wanita boleh bekerja, Islam tidak melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, perempuan pada zaman Nabipun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Tetapi masalahnya bukan adanya hak atau tidak karena Islam tidak cenderung untuk membenarkan wanita keluar rumah. Kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Kebutuhan wanita untuk bekerja mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya merupakan alasan yang menetapkan adanya hak bakerja untuk wanita, dengan catatan bahwa ia bisa menjaga norma-norma agama dan kehormatan.19
Penafsiran Ibnu Katsir lebih moderat, menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat misalnya.20
Al-Maududi dalam
al-Hijabnya berpendapat bahwa ayat tersebut memang perintah untuk tinggal di rumah, tetapi perintah tersebut tidak dipandang sebagai batasan yang kaku, wanita yang tidak mempunyai handai tolan atau yang suaminya lemah bisa bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah demi menghidupi dirinya dan keluarganya.21
Berbeda halnya dengan Muhammad Husain at-Thabāthabā‟Ī dalam
Tafsīr al-Mīzān-nya, memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ayat yang tersebut di atas. Menurutnya bahwa kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir
(quwwat al-ta’aqqul) yang karena itu, melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara wanita sensitif dan emosional.22
At-Thabāthabā‟Ī adalah seorang ulama pemikir, fiqh, filosofis dan ahli matematika, banyak mengeluarkan karya penting dalam bidang ilmu kefilsafatan Islam termasuk di dalamnya karya monumentalnya yakni
Tafsīr al-Mīzān. Kemudian
Tafsīr fī Dzilālil Qur’ān adalah karya Sayyid Quthb, seorang sastrawan yang terkenal, sebagai seorang sastrawan tulisan-tulisannya memiliki ruh dan juga sangat menarik di kalangan luas. Sebuah kitab yang ditulis di penjara, ketika Sayyid Quthb hidup dalam nuansa iman.23
Objek penelitian ini adalah penafsiran Sayyid Quthb dan at- Thabāthabā‟Ī, pilihan ini dikarenakan metode tafsīr yang digunakan oleh Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā‟Ī menurut penulis keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur‟ān tersebut. Menurut Sayyid Quthb wanita tidak harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka, yang selain daripada itu adalah sekunder. Sedangkan menurut at-Thabāthabā‟Ī bahwa wanita itu harus menetap dan tinggal di rumahnya kecuali sebuah kepentingan.
Persoalannya sekarang, apakah peranan wanita hanya disektor domestik? Apakah peranan di sektor publik masih dibatasi?24 Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam skripsi ini.
1 Sri Suhandjati Sukri, (ed.),
Pemahaman Islam dan Tantangan
Keadilan Jender, Gama Media, Yogyakarta, 2002.
2 Murtadha Muthahhari,
Hak-hak Wanita Dalam Islam, terj: M. Hasyem, Lentera, Jakarta, cet. V, 2000, hlm. 75.
3 Bustami A. Gani, dkk,
Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur’ān,
yang disampaikan oleh Drs. Hj. Aisyah Dachlan , Pustaka Litera ntar Nusa, Jakarta, cet. II, 1994, hlm. 195.
4 Murtadha Muthahhari
, op. cit., hlm. 76.
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’ān dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟ān, Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 672.
6 Afifah Afrah, Panduan Amal Wanita Salihah, Afra Publishing
Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi, Surakarta, 2008, hlm. 344.
7 Muhammad bin Ismā‟il al-Bukhāry, Sahih al-Bukhāry, Maktabah
Dahlan, Surabaya, t.th., III: 2166.
8 Yusuf Qardhawi,
Qardhawi Bicara Soal Wanita, terj. Tiar Anwar
Bachtiar, Arasy, Bandung, 2003, hlm. 92-93.
9 Maisar Yasin,
Wanita Karier Dalam Perbincangan, Gema Insani
Press, Jakarta, cet. IV, 2003, hlm. 30-31.
10 Afifah Afrah,
Panduan Amal Wanita Salihah, Afra Publishing
Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi, Surakarta, 2008, hlm. 345.
11 Siti Hariati Sastriyani, Women In Public Sector (Perempuan di
Sektor Publik), Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2005, hlm. 238.
12 Siti Muri‟ah, Nilai-nilai Pedidikan Islam dan Wanita Karier,
Rasail Media Group, Semarang, 2011, hlm. 199.
13 Ibid., hlm. 337.
14 M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan
Keserasian Al-Qur’ān), Lentera Hati, Jakarta, cet. VI, 2002, hlm. 469.
15 Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias
Gender Dalam Tradisi Tafsīr, terj: Abdullah Ali, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta,
2001, hlm. 79.
16 Amina Wadud, loc. cit.
17 Ahmad Musthāfā al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī, juz VII, Dar al- Fikr, Beirut, 1974, hlm. 5.
18 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’ān Tafsīr Maudhu’i Atas
Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 1994.
19 Quraish Shihab, Konsep Wanita Menurut Qur’an Hadits dan
Sumber-sumber Ajaran Islam, INIS, Jakarta, 1993, hlm. 11.
20 Ibnu Katsir, Tafsīr Al-Qur’ān Al-Adzīm, juz III, Sulaiman Mar‟i,
Pinang, t.th., hlm. 523.
21 Al-Maududi, Al-Hijab, Gema Risalah Press, Jakarta, 1993, hlm.
210.
22 At-Thabāthabā‟Ī,
Tafsīr Al-Mīzān, juz IV, Mu‟assasah al‟alawi li
al-mathbuat, Beirut, 1911, hlm. 351.
23 Shalah Abdul Fatah al-Khalidi,
Pengantar Memahami Tafsīr fī
Dzilālil Qur’ān Sayyid Quthb, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Intermedia, Solo,
2001, hlm. 13.